Dengan
berdasarkan pada pengetahuan yang benar dan tepat tentang pemahaman apa yang
layak dan yang tak layang, mengenai kebenaran berbeda dari ketidak benaran,
seorang hakim memulai pemeriksaannya (M.VIII.24). Menurut pasal ini, pasal 24
Bab VIII. Manusmrti, seorang hakim Brahmana harus benar-benar ahli yang
mendalami kebenarankebenaran dharma yang harus ditegakkan. Dengan melihat atas
dasar kata mata ilmu, dan Dharma (sruti, smrti, acara, sila dan atmanastuti serta
segala UU dan peraturan yang berlauku) hakim memeriksa setiap gugatan yang
diajukan kepadanya. Ditinjau dari segi
pembuktian itu, dianut beberapa jenis bukti. Maha Rsi Yajnawalkya dalam
tulisannya mengemukakan ada empat macam bukti, yaitu:
1) Lekhya (bukti
autentik atas tertulis)
2) Bhukti (Bukti
pemilihan atas materiil)
3) Saksi (bukti
saksi)
4) Diwya (bukti
sumpah)
Diantara semua bukti Lekhya dianggap paling kuat. Lekhya tidak hanya merupakan dokumen tertulis. Bukti pemilihan atau Bhukti merupakan alat pembuktian yang kuat pula kecuali kalau barang bukti itu sendiri ditolak, diperlukan adanya bukti lainnya seperti saksi. Saksi dalam pembuktian diperlukan untuk memperkuat dalil-dalil dan hasil-hasil pembuktian yang ada. Kedudukan dan peranan saksi ditentukan secara panjang lebar pula didalam Kitab dharma sastra itu, seperti syarat-syarat seorang saksi, sangsi-sangsi bagi pemberi kesaksian palsu dan sebagainya. Demikian pula tentang cara-cara pemeriksa saksi dan kesaksian yang diberikan. Menurut Bhagawan Manu, dalam pembuktian mempergunakan saksi, Bab VIII 60-71 ditetapkan pokok-pokok pemikiran sebagai berikut:
1)
Setidak-tidaknya harus diketengahkan tiga saksi.
2) Saksi harus
telah berumah tangga. Pengertian berumah tangga dalam ayat-ayat itu adalah
dewasa.
3) Saksi diberikan
oleh para pihak
4) Saksi harus
bebas dari lobha
Diwya asal mulanya merupakan kesaksian Dewa-dewa, yaitu minta kesaksian dari Dewa atas perkara itu pembuktian yang disampaikan. Jadi diwya adalah semacam saksi pula yang dalam pelaksanaannya dipraktekkan dalam bentuk sumpah dengan meminta kekuatan Tula, Agni, Apah, Wisa atau kosa. Pengambilan sumpah menurut masing-masing cara diatas tidak sama, menurut maksud yang terkandung dalam arti kata yang dipakai.
Sumpah menurut
sistem Tula timbangan, dimana yang disumpah ditimbang dengan pemberat lainnya.
Sebaliknya sumpah menurut Agni, yang disumpah ditest dengan api. Bila terbakar
dianggap bersalah. Contoh klasik dalam cerita Ramayana. Apah atau sumpah
dengan air, yang ditenggelamkan ke dalam air untuk beberapa waktu. Bila dapat
bertahan atau hidup dianggap tidak bersalah. Wisa atau sumpah dengan
racun. Dalam bahasa daerah di Bali dikenal dengan nama Mecor atau
disumpah dengan minum racun. Bila hidup berarti tidak bersalah.
Kosa adalah sumpah semacam Wisa hanya saja tidak beracun, melainkan dengan memakai air bekas pembersih arca atau keris yang telah dimantrai kemudian dimandikan dan diminum tiga teguk. Bila tidak mempunyai akibat apa-apa dalam beberapa waktu yang lama dianggap tidak salah. Berbagai jenis sumpah di atas telah dibuang dan mengalami banyak perubahan dan bahkan ada yang ditinggalkan atau ditiadakan. Kecuali dalam hal pidana-pidana berat kadang-kadang masih dipergunakan sumpah-sumpah seperti itu. Dewasa ini bentuk sumpah yang lebih ringan adalah jenis sumpah bentuk separtha, yaitu sumpah hanya dalam katakata, missal : kata benar saya bersalah supaya tidak selamat.”supaya tidak bahagia dan sebagainya”. Hanya ciri-ciri kekhasan agama masih sering dikedepankan misalnya bersumpah dihalaman pura, minta kesaksian dewa-dewa dan sebagainya.
Konkritisasi hukum Hindu dalam peradilan telah dimulai sejak jaman Manu, melalui pengadilan Brahmana. Skala berikut ini membenarkan adanya pengadilan Brahmana tersebut : pengadilan yang dilakukan oleh tiga orang Brahmana ahli dalam Weda dan seorang hakim ahli yang ditunjuk oleh raja dinamakan Pengadilan Brahmana (Manu VIII : 11). Raja dinyatakan menyelidiki dan memutuskan langsung setiap perkara, tetapi bila berhalangan, ia dapat menunjuk Brahmana ahli untuk mengadilinya. Setiap pelanggaran hukum dituduhkan pada delapan belas titel hukum (Wyawahara-pada), sebagaimana dinyatakan dalam sloka berikut ini : “begitulah cara menyelesaikan perkara yang termasuk kedalam delapan belas titel, antara dua pihak yang berperkara yang telah dinyatakan panjang lebar” (Manu, IX :250). Pengadilan Brahmana yang dikenal pula sebagai Parisad atau Majelis. Diteruskan keberadaannya dalam jaman-jaman raja-raja di India. Kautilya menginformasikan adanya pengadilan-pengadilan majelis pada jaman raja-raja di India, raja masih tetap mempunyai kewenangan sebagai orang hakim (raja menjadi kepala Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif).
Dalam prinsip kerajaan yang ditinggalkan Kautilya, seorang hakim dinyatakan harus memegang Dharma atau kebenaran. Dalam perkembangan selanjutnya, hukum Manu berpengaruh sekali pada bentuk hukum dan perundang-undangan Majapahit. Ini secara dinyatakan langsung dalam kitab Kutara Manawa yang dijadikan sebagai kitab perundang-undangan dalam kerajaan Majapahit di Jawa Timur, terutama pada jaman pemerintahan Dyah Hayam Wuruk Sri Rajasanegara. Dalam susunan pengadilan kita juga mengenal adanya Dhyaksa. Seorang Dharmadhyaksa Kasaiwan, seorang Dharmadhyaksa Ksakasogatan, yakni agama Siwa dan peminpin agama Budha dengan sebutan Dang Acarya, karena kedua agama itu merupakan agama utama dalam kerajaan Majapahit dan segala perundang-undangan didasarkan pada agama. Sang Dharmadhyaksa dibantu lagi oleh lima
Upapatti artinya : pembantu yang dalam piagam biasa disebut pemegat, baik Dharmadhyaksa maupun Upapatti disebut juga dengan Acarya. Upaptti ini dalam perkembangan selanjutnya jumlahnya makin banyak. (Slametmulya, 1979, 189-195). Sampai di sini jelas sekali adanya gambaran hakim majelis yang melibatkan Dang Acarya, sebagai orang suci yang tidak diragukan lagi kejujurannya, integritas dan dapat melihat kebenaran yang hakiki.
Kerajaan Majapahit
dalam sejarah kita kenal berhasil mempersatukan Nusantara yang sekarang kita
warisi sebagai Negara Kesatuan Indonesia. Pada setiap wilayah jajahannya,
Majapahit nampaknya selalu berusaha menanamkan segala pengaruhnya, termasuk
pengaruh dalam bidang hukum. Di Bali pengaruh ini kentara sekali, meskipun
dalam penerapannya banyak mengalami modifikasi. Terutama materi hukumnya yang
disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan penduduk setempat. Gede Pudja
mengatakan bagian-bagian dari ajaran-ajaran dan pasal-pasal dalam Dharmasastra
telah diambil alih dan dipergunakan sebagai hukum pada masa kerajaan Hindu di Indonesia.
Bukan pada masa kerajaan Hindu saja, karena secara tidak disadari bahwa hukum
itu berpengaruh dan masih tetap berlaku pada hukum positif di Indonesia melalui
bentuk-bentuk hukum adat. Bentuk acara hukum dan kehidupan hukum Hindu yang
paling nyata masih terasa sangat berpengaruh adalah bentuk hukum adat di Bali
dan Lombok, sebagai hukum yang berlaku bagi golongan Hindu sematamata (Gde
Pudja, 1977 : 34). Pada jaman Bali kuna, kerajaan-kerajaan di Bali seperti di
masa kejayaan Jayapangus dilengkapi pula dengan Lembaga Peradilan. Ini membuktikan
dari peran pendeta sebagai saksi dalam persidangan sebagaimana dinyatakan dalam
prasasti Kediri 629 B.Via. (Sukarto K.Atmojo dalam SA.Ketut Renik, 1988:15).
Dalam bait (1) dari prasasti: ....telah dipersaksikan di depan tandarakyan rin
pakiran kiran, (2) ijro makabehan seperti para senopati terutama para pendeta
Siwa dan Budha. Yang hadir pada waktu itu senopati Belambunut. Persaksian semacam
itu dapat terbaca pula dalam prasasti 350 Abang Pura Batur A (933 S).
Majalah Universitas Udayana, XV No. 18,198:15-16). Masa-masa setelah berakhirnya periode Bali kuna, kita mewarisi adanya pengadilan desa tiap-tiap desa di Bali. Para hakim yang bertindak memutuskan perkara-perkara biasanya ditangani atau diambil-alih langsung oleh para tetua desa dan orang-orang yang dianggap tahu tentang hukum Adat atau kebiasaan-kebiasaan setempat yang bersumber pada ajaran-ajaran agama. Tidak dijumpai catatan tertulis mengenai hukum yang diterapkan pada kesepakatan bersama warga desa yang sudah turun temurun. Tetapi setiap keputusan biasanya ditundukan. Sampai kepada kedatangan Belanda di tahun 1849, yang ditandai dengan perang Jagaraga, pengadilan Kerta di Bali, terutama sebelum tahun 1930, para tetua desa sering diminta pendapatnya mengenai berbagai sengketa yang timbul di masyarakat. Atau dapat juga persoalan-persoalan itu diajukan kepada para brahmana ahli. Peradilan kerta di Bali dibangun 33 tahun, terhitung sejak perang Jagaraga tahun 1849, tepatnya tahun 1882 (Buleleng) dan (Jembrana). Raad Kerta-Raad Kerta di kabupaten lain, dibangun menyusul belakangan, Karangasem tahun 1894, Klungkung 1910, Gianyar dan Bangli tahun 1916. Dalam penelitian Raad Kerta di Bali merupakan konkritisasi nilai-nilai hukum Hindu ini dibuktikan dari kitab-kitab hukum-hukum yang dijadikan pegangan para hakim Kerta, seperti Agama, Adigama, Purwagama, Manawa Swarga, dan Kutaragama serta kitab-kitab hukum yang lain. Yang banyak mengacu hukum Manu atau Weda Smrti. Demikian gambaran mengenai konkritisasi hukum Hindu dalam peradilan sejak jaman Manu sampai pada jaman pemerintahan Hindia Belanda di Indonesia.









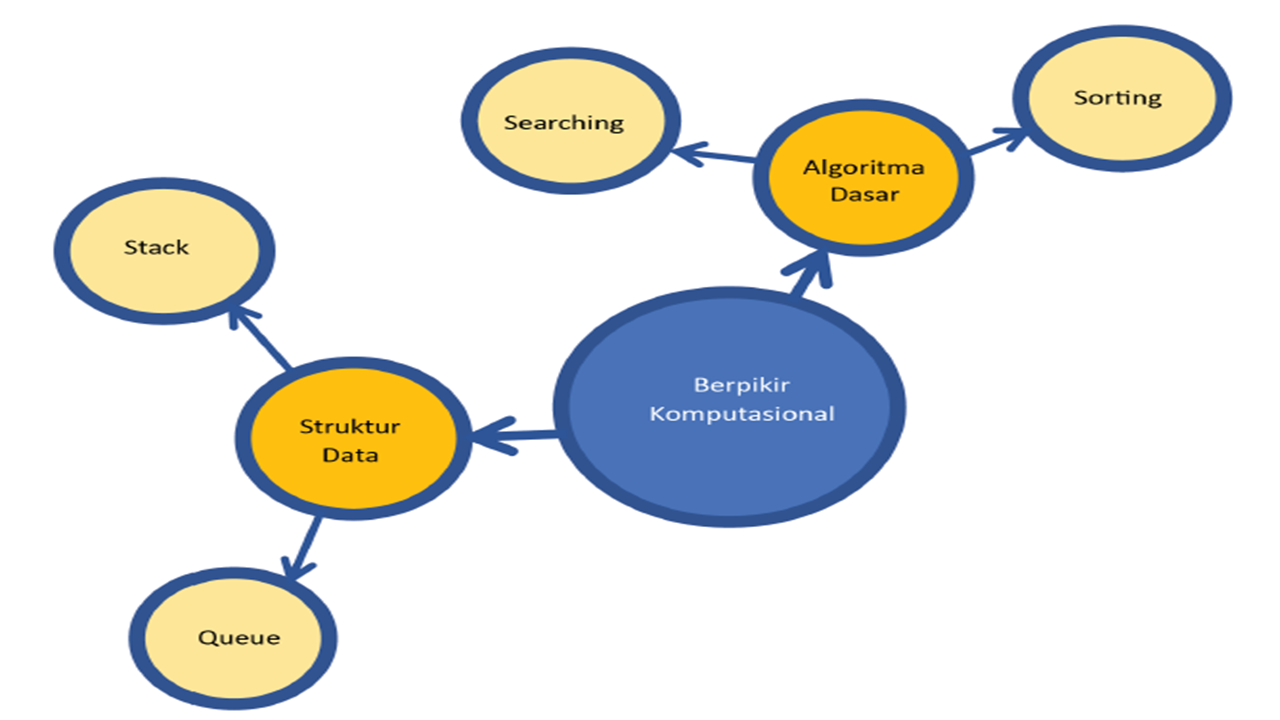



Komentar
Posting Komentar